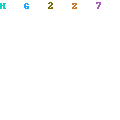Mau MInum APa?
Suatu hari, Udin berkunjung ke rumah Didin, temannya sewaktu sama-sama mondok. Sejak pulang ke rumah tujuh belas tahun yang lalu, keduanya belum pernah sekalipun bertemu. Maklum di samping jarak kota yang berjauhan, ditambah banyaknya kesibukan membuat keduanya tidak berjumpa hingga belasan tahun lamanya.
Seperti sebuah kebetulan, Udin ada urusan yang harus diselesaikan di kota tempat tinggal Didin. Nah, kesempatan ini tak boleh aku sia-siakan, tekad Udin dalam hati.
Setelah semua urusan beres, mulailah si Udin mencari alamat Didin, sahabat yang dirindukannya. Awal mulanya agak sulit karena Didin ternyata sudah pindah alamat, namun dengan tekadnya yang besar, akhirnya bertemulah keduanya.
”Ahlan wa sahlan!!!” teriak Didin begitu melihat Udin di depan pintu. Keduanya berpelukan lama kemudian terlibat dalam obrolan hangat.
”Sebentar” ujar Didin, ”Aku belum Sholat nih! Biar ngobrolnya enak, kau di sini dulu, aku Sholat dulu. Ok?
”Ok. Aku tadi sudah Sholat di Masjid”
“Tomo!” Didin memanggil pembantunya.
“Ya, mas!” Tomo datang menghadap.
“Ini temanku, Ustadz Udin namanya. Aku mau Sholat dulu, tolong layani dia sebaik-baiknya”
“Ya mas!” Didin berlalu…
“Ustadz minum kopi, teh atau susu?”
”Kopi saja”
”Kopinya kopi arab, kopi tubruk, kopi jahe atau…”
”Apa ajalah”
”Pake gula, krim, madu?”
”Gula”
”Pake susu?”
”Boleh”
”Susu sapi, susu onta, susu kambing?”
”Susu sapi”
”Sapi perah, sapi Australi…”
”Sudah-sudah, saya minum air putih saja”
“Merk aqua, ades…”
“Apa aja deh. Terserah kamu!”
”Rasa anggur, strawberry…”
”Gini aja, aku gak minum. Capek pengen istirahat!” tukas Udin kesal sambil meletakkan kepalanya pada sandaran kursi.
Suara GorenGAn ?
Angin sepoi-sepoi menghembus di daerah pegunungan yang cukup dingin dan menyejukan. Hamparan pegunungan indah, hijau dan luas itu melengkapi indahnya panorama desa yang terkenal dengan petani kentangnya.
Namun daerah ini tampaknya kurang mendapat pendidikan agama. Berdasarkan informasi itulah, sekelompok pengurus pesantren dari luar kota dengan menggunakan mobil mendatangi desa tersebut. Mereka langsung menuju rumah tokoh kampung setempat.
“Assalamu’alaikum”, salam mereka. “Wa’alaikumsalam”, jawab Pak Hari. Setelah mereka dipersilahkan duduk, seorang dari mereka memulai pembicaraan. “Pak Hari, tujuan kami datang ke sini untuk menugaskan para santri kami yang ingin melaksanakan study tour ke desa ini”. “Oh iya saya selaku tokoh di desa ini merasa terhormat dan bahagia dengan kabar ini” ujarnya.
Perbincangan pun makin asyik dan hangat. Kegembiraan diantara keduanya terpancarkan dari wajah dan cara mereka berbicara. Hingga sekitar 3 jam lebih mereka berbincang-bincang, namun tidak ada satupun hidangan yang dikeluarkan. Rombongan dari pesantren ini mulai gelisah.
Di tengah-tengah kegelisahan mereka, Pak Hari berkata. “Bagaimana kalau anda sekalian mendengarkan qosidah yang akan saya bawa”. Kemudian dengan nada kesal seorang diantara mereka berkata. “Maaf pak! Bukannya kami tidak mau mendengarkan suara anda yang merdu itu, tapi kami lebih ingin mendengarkan suara ikan anda digoreng.”
MentrI tAhajjuD SianG mALam !!
Dalam suatu acara halaqah di sebuah pesantren di Jawa Timur yang dihadiri para Kiai, seorang menteri yang sangat terkenal datang memenuhi undangan panitia. Konon kabarnya, kedatangan menteri tersebut di samping akan memberikan sambutan juga diharapkan bisa memberikan sumbangan ala kadarnya bagi pembangunan di pesantren.
Selang beberapa menit acara dibuka oleh pemandu acara, tibalah saatnya Bapak Menteri mendapat giliran memberikan sambutan. Seperti biasa dalam acara-acara formal setelah memberi salam dan kata penghormatan secukupnya, Pak Menteri itu sampai pada isi sambutannya.
“Saudara-saudara sekalian yang terhormat,” katanya.
“Meskipun Bapak-bapak Kiai yang ada di sini Tahajjud siang-malam belum tentu lebih mulia dari seorang yang mengerti teknologi,” lanjutnya dengan sangat berapi-api.
Sontak, para hadirin dibikin geger dengan sambutan itu. Menit berikutnya para Kiai satu demi satu meninggalkan ruang pertemuan. Mereka tidak mau mendengarkan sambutan Pak Menteri yang rajin Puasa Senin-Kamis itu.
Usut punya usut ternyata ketersinggungan para Kiai bukan karena Pak Menteri sudah melecehkan keberadaan mereka di mata para Santri. Para Kiai tersinggung karena Pak Menteri salah ucap.
“Mana ada Tahajjud siang-malam,” kata seorang Kiai sambil menggerutu.
SuAra TUHAN !!
Sejak masih muda KH. Amanullah (Tambak Beras) memang terkenal sebagai santri yang cerdik dan banyak akal. Pada waktu masih muda banyak diantara teman-teman santrinya yang suka menjalankan riyadlah’ dengan melakukan puasa, wirid dan sebagainya. Hal ini dilakukan selain sebagai upaya mensucikan kondisi spiritual (batin) juga sebagai upaya memperoleh berkah dari Allah.
Pada suatu hari ada seorang santri yang sedang melakukan riyadlah (olah rohani). Mengetahui hal ini Gus Aman (panggilan akrab KH. Amanullah) bertanya pada yang bersangkutan: “Kapan sampeyan telasan (berakhir) melakukan riyadlah?” Santri tersebut menyatakan bahwa telasannya malam Jum’at. Mendengar jawaban tersebut Gus Aman menyarankan agar wirid telasan dilakukan di sudut imaman Masjid, agar do’anya makbul.
Pada malam yang ditentukan, santri tersebut benar-benar menjalankan saran Gus Aman. Tepat jam 01.00 malam dia wirid dan berdo’a dengan sangat khusu’nya. Diam-diam Gus Aman ngintip dari lubang ventilasi. Kemudian dengan suara yang dibuat bergetar Gus Aman bilang : “njaluk opo ngger?” (minta apa cucuku).
Mendengar pertanyaan ini sang santri langsung teriak sambil menangis : “Ya Allah, kulo nyuwun ilmu ingkang manfa’at, nyuwun akal ingkang padang, nyuwun rizqi ingkang kathah lan derajad ingkang murwat.” (Ya Tuhan, aku mohon ilmu yang bermanfaat, akal yang jernih, rizki yang banyak dan derajat tinggi).
Dengan bergetar Gus Aman menyahut : “Yoh, tak sembadani!” (Ya, aku kabulkan…)
Saking percayanya terhadap suara tersebut, santri ini langsung sujud dan menangis : “Matur nuwun Gusti, matur nuwun,” (Terima kasih…) teriaknya keras-keras. Setelah itu dia melakukan Shalat Sunnah hingga datang fajar.
Siang harinya, ketika Gus Aman lewat di depan santri tersebut, dengan suara bergetar bilang : “njaluk opo ngger.” Mendengar suara ini santri tersebut baru sadar bahwa semalam dia dipermainkan. Paham kalau diejek kemudian dia mengejar Gus Aman sambil membawa pentung.
kYAi biSRi & kYai wAHab !!
Meski sama-sama pemegang fikih yang ketat, Kiai Wahab dan Kiai Bisri berbeda strategi penerapannya. Kiai Wahab cenderung bergaris lunak, sementara Kiai Bisri bergaris keras.
Suatu hari menjelang Idul Adha seseorang datang menghadap Kiai Bisri. Dia bermaksud melaksanakan kurban dengan menyembelih seekor sapi. Namun sebelumnya dia berkonsultasi dulu dengan Kiai Bisri, apakah boleh berkurban seekor sapi untuk 8 orang? Ketentuan fiqih, 1 sapi untuk 7 orang. Padahal jumlah keluarganya ada delapan. dia ingin di akhirat nanti satu keluarga itu bisa satu kendaraan agar tidak terpencar.
Mendengar pertanyaan tersebut Kiai Bisri menjawab “tidak bisa”. Kurban Sapi, Kerbau atau Unta hanya berlaku untuk 7 orang. Kemudian orang itu menawar pada Kiai Bisri, “Pak Kiai, apakah tidak ada keringanan. Anak saya yang terakhir baru 3 bulan”. Dengan menjelaskan dasar hukumnya, Kiai Bisri tetap menjawab, tidak bisa.
Merasa tidak puas, orang itu mengadukan persoalannya kepada Kiai Wahab di Tambak Beras. Mendengar persoalan yang diadukan orang itu Kiai Wahab, dengan ringan menjawab, “Bisa. Sapi itu bisa digunakan untuk 8 orang, Cuma karena anakmu yang terakhir itu masih kecil, maka perlu ada tambahan.” Mendengar jawaban Kiai Wahab orang itu tampak gembira.
“Agar anakmu yang masih kecil itu bisa naik ke punggung Sapi, harus pakai tangga. Sampeyan sediakan seekor Kambing agar anak sampeyan bisa naik ke punggung sapi.”
“Ah, kalau cuma seekor Kambing saya sanggup menambah. Dua ekor pun sanggup asal kita bisa bersama-sama, Kiai.”
Akhirnya pada hari kurban, orang tersebut menyerahkan seekor Sapi dan seekor Kambing pada Kiai Wahab.
Di daerah Kandangan Rembang, dulu ada seorang Kiai desa sederhana. Sudah tua tapi aktif sekali. Dimana saja ada peristiwa penting beliau selalu tampak. Misalnya di konferensi NU Wilayah, di muktamar NU. Padahal melihat penampilannya tidak meyakinkan. Sehingga terbetik kepercayaan bahwa Mbah Sungeb mempunyai aji-aji sampar angin.
Suatu ketika, Mbah Sungeb dan beberapa Kiai naik kendaraan umum pulang ke Rembang. Karena kendaraan mogok, mereka terpaksa berjalan kaki. Padahal Rembang masih jauh sekali.
Seorang Kiai ingat, bahwa Mbah Sungeb -konon- punya aji-aji sampar angin. Sambil sama-sama berjalan kaki, Kiai muda itu bertanya, “Kalau pergi ke Situbondo, Semarang, Yogya itu pakai aji-aji apa mbah kok bisa cepat sampai, bisa mendahului yang pakai sedan”. Beliau menjawab seperti sekenanya saja : “li ila”. (ayat li ila fi quraisyin…)
Mendengar itu Kiai lain berkomentar. “Itu tidak ada haditsnya. Yang ada itu Surat Fatihah. Fatihah itu bisa untuk keperluan apa saja. Misalnya kita ingin jalan cepat tanpa capek, baca saja Fatihah.
Kiai lain menengahi. “Begini saja, Mbah Sungeb ini sudah punya “li ila” supaya jalan cepat. Biarkan Mbah Sungeb pakai “li ila”. Sampeyan pakai Fatihah. Nanti saya ikut mana yang paling cepat”.
Baru saja mereka berdebat, tiba-tiba datang seorang anak muda dari belakang naik sepeda motor menegur Mbah Sungeb.
“Mau kemana, Mbah?
“Ke Rembang”
“Mari ikut saya”.
Mbah Sungeb pun lalu membonceng sepeda motor anak muda itu.
Dua Kiai yang lain tetap berjalan kaki. Sambil menahan lelah, Kiai muda tadi bilang kepada temannya, “Ternyata lebih mujarab “li ila”-nya Mbah Sungeb daripada punya sampeyan”.